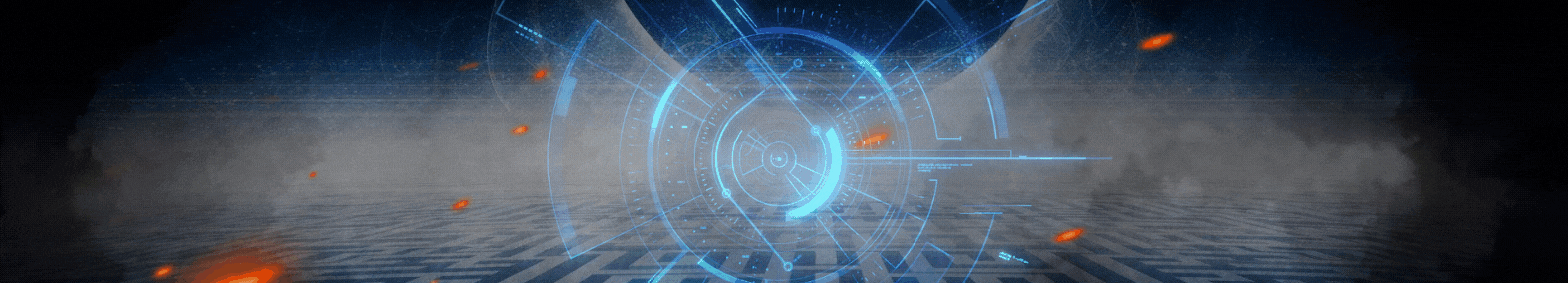Oleh:
Lili Agustiani
Polres Bontang memediasi konflik antara nelayan dari Bontang Lestari dan Santan Ilir dengan PT Energi Unggul Persada (EUP) terkait dugaan pencemaran lingkungan di perairan sekitar. Perwakilan aliansi nelayan Muara Badak, Nina, menyatakan bahwa pencemaran telah berlangsung selama setahun terakhir, namun baru kali ini dampaknya terlihat signifikan dengan banyaknya ikan yang mati. Nelayan menuntut ganti rugi dan perbaikan lingkungan jika terbukti terjadi pencemaran. https://radarbontang.com/
PT EUP melalui Humasnya, Jayadi, membantah tuduhan pencemaran tersebut. Mereka berpendapat bahwa kematian ikan disebabkan oleh faktor lain seperti arus laut, kekurangan oksigen, atau bahkan sabotase. Perusahaan mengklaim telah mengikuti prosedur operasional yang sesuai dan tidak menemukan bukti pencemaran dari aktivitas mereka. https://radarbontang.com/
Meskipun mediasi telah dilakukan, belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak. Nelayan tetap menuntut tanggung jawab dari PT EUP atas kerugian yang mereka alami, sementara perusahaan bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik lingkungan antara masyarakat dan perusahaan.
Kasus pencemaran laut di Bontang bukan sekadar persoalan teknis limbah atau konflik lokal antara nelayan dan perusahaan. Ini adalah cermin nyata dari relasi timpang antara rakyat kecil dan korporasi raksasa dalam sistem kapitalisme. Di bawah sistem ini, laut dan sumber daya alam dipandang semata sebagai komoditas ekonomi yang boleh dieksploitasi sebebasnya demi akumulasi profit, meskipun dengan mengorbankan hak hidup masyarakat pesisir. Nelayan yang seharusnya menjadi penjaga laut justru menjadi korban paling awal dari kerakusan ini.
Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru seringkali berubah menjadi perpanjangan tangan korporasi. Dalam sistem kapitalis, negara cenderung berpihak pada investasi dan kepentingan ekonomi elite ketimbang memastikan keadilan bagi rakyat. Mediasi yang dilakukan aparat tak lebih dari formalitas untuk menjaga citra stabilitas, tanpa menyentuh akar masalah sesungguhnya. Sementara nelayan dipaksa bernegosiasi di meja mediasi, perusahaan tetap leluasa menjalankan aktivitasnya. Apakah ini yang disebut keadilan?
Pola seperti ini bukan hal baru. Kapitalisme telah lama melahirkan sistem hukum yang berat sebelah—di mana korporasi punya kekuatan finansial dan politik untuk memanipulasi narasi, menyewa ahli, bahkan membeli pembenaran ilmiah demi menghindari tanggung jawab. Lihat saja bantahan PT EUP yang justru menyalahkan arus laut dan oksigen, tanpa ada itikad transparan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dalam kapitalisme, tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya berlaku selama tidak mengganggu profit. Jika konflik muncul, maka yang pertama dikorbankan adalah hak rakyat.
Terlebih lagi, dalam sistem ini, alam bukan dipandang sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga, melainkan aset yang harus diolah untuk mencetak laba. Maka tidak heran, pencemaran bisa berlangsung setahun tanpa tindakan berarti. Ketika akhirnya meledak, penanganannya pun bersifat reaktif dan parsial. Inilah watak sistemik dari kapitalisme: membiarkan kerusakan terjadi selama tidak mengganggu stabilitas ekonomi elite. Padahal, keadilan hakiki tak akan pernah lahir dari sistem yang menjadikan materi sebagai tujuan tertinggi.
Islam memandang alam bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Dalam sistem Islam, laut, sungai, udara, dan tanah tergolong kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) yang tidak boleh dikuasai atau dieksploitasi oleh individu maupun perusahaan atas nama investasi. Negara dalam Islam berperan sebagai pengelola, bukan pemilik, yang wajib memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tidak merusak ekosistem dan tidak mencelakai masyarakat.
Berbeda dengan kapitalisme yang memprioritaskan keuntungan, sistem Islam mengedepankan maslahat umat dan prinsip tanggung jawab. Jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, negara Islam akan segera bertindak tanpa harus menunggu desakan publik. Penguasa dalam Islam adalah ra’in (pelayan rakyat) dan junnah (pelindung), yang akan mengadili perusahaan atau individu yang melakukan kerusakan (fasad fil ardh) dengan tegas, karena merusak lingkungan dalam Islam termasuk dosa besar yang bisa dikenai sanksi pidana.
Lebih jauh, negara dalam sistem Islam tidak akan menjadikan laut sebagai objek eksploitasi pasar bebas atau dikuasai korporasi. Pengelolaan wilayah pesisir akan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk nelayan, dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Islam juga melarang monopoli dan privatisasi terhadap harta milik umum, sehingga potensi kerusakan akibat aktivitas industri besar bisa diminimalisir. Dengan cara ini, rakyat tidak akan menjadi korban dari sistem yang membiarkan keserakahan berlangsung.
Solusi Islam bersifat preventif sekaligus solutif. Preventif, karena dengan syariat yang jelas, negara mencegah kerusakan sejak awal. Solutif, karena jika terjadi pelanggaran, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu—baik terhadap individu maupun korporasi. Maka, untuk benar-benar menghentikan lingkaran kerusakan dan ketidakadilan seperti yang dialami para nelayan di Bontang, kita tidak cukup hanya memperbaiki regulasi, melainkan harus keluar dari sistem kapitalisme yang cacat sejak akar, dan menggantinya dengan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Wallahu’alam Bishowab